#MenolakLupa!! #JanganAmnesia!!! Poso, Kenangan Kelam Yang Terabaikan
“Menolak
Lupa! Poso dan Tragedi Kemanusiaan”
Kita percaya keberagaman dan toleransi harus dimenangkan – Jerinx
Oleh
Aris Rasyid Setiadi
Ketika menyebut nama Poso, sontak yang terbayang
dalam benak kita ialah konflik dan konflik. Ya, sebagaimana Aceh dan Papua,
Poso memang rawan konflik. Tragedi kemanusiaan acap kali terjadi di sana.
Konflik berdarah Islam-Kristen seolah mempertegas bahwa Poso memang potensial
melahirkan kekerasan.
Poso adalah sebuah kabupaten yang terdapat di
Sulawesi Tengah. Kalau dilihat dari keberagaman penduduk, Poso tergolong daerah
yang cukup majemuk, selain terdapat suku asli yang mendiami Poso, suku-suku
pendatang pun banyak berdomisili di Poso, seperti dari Jawa, batak, bugis dan
sebagainya.
Suku asli asli di Poso, serupa dengan daerah-daerah
disekitarnya; Morowali dan Tojo Una Una, adalah orang-orang Toraja. Menurut
Albert Kruyt terdapat tiga kelompok besar toraja yang menetap di Poso. Pertama,
Toraja Barat atau sering disebut dengan Toraja Pargi-Kaili. Kedua adalah Toraja
Timur atau Toraja Poso-Tojo, dan ketiga adalah Toraja Selatan yang disebut juga
denga Toraja Sa’dan. Kelompok pertama berdomisili di Sulawesi Tengah, sedangkan
untuk kelompok ketiga berada di Sulawesi Selatan. Untuk wilayah Poso sendiri,
dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah Poso tojo yang berbahasa
Bare’e dan kedua adalah Toraja Parigi-kaili. Namun untuk kelompok pertama tidak
mempunyai kesamaan bahasa seperti halnya kelompok pertama.
Kalau dilihat dari konteks agama, Poso terbagi
menjadi dua kelompok agama besar, Islam dan Kristen. Sebelum pemekaran,
Poso didominasi oleh agama Islam, namun setelah mengalami pemekaran menjadi
Morowali dan Tojo Una Una, maka yang mendominasi adala agama Kristen. Selain
itu masih banyak dijumpai penganut agama-agama yang berbasis kesukuan, terutama
di daerah-daerah pedalaman. Islam dalam hal ini masuk ke Sulawesi, dan
terkhusus Poso, terlebih dahulu. Baru kemudian disusul Kristen masuk ke Poso.
Keberagaman ini lah yang menjadi salah satu pemantik
seringnya terjadi berbagai kerusuhan yang terjadi di Poso. Baik itu kerusuhan
yang berlatar belakang sosial-budaya, ataupun kerusuhan yang berlatarbelakang
agama, seperti yang diklaim saat kerusuhan Poso tahun 1998 dan kerusuhan tahun
2000. Agama seolah-olah menjadi kendaraan dan alasan tendesius untuk kepentingan
masing-masing.
Poso, memang tidak aman. Sejak bulan Desember 1998
yang silam, Poso telah bergolak. Kemudian, berlanjut pada tragedi April 2000
yang dikenal dengan “Kerusuhan Poso II” dan “Kerusuha Poso III” yang
berlangsung tanggal 26 Mei sampai 15 Juni 2000. Dalam tragedi berdarah itu,
korban yang jatuh mencapai 300 lebih.
Tragedi Poso di tahun 1998 bermula dari penganiayaan
Roy Runtu (Kristiani) terhadap Ridwan Ramboni (Muslim). Peristiwa ini terjadi
tepat di Hari Natal, yakni pada hari Jum’at tanggal 25 Desember 1998.
Penganiayaan itu dilakukan di masjid Darussalam Kel. Sayo. Sontak saja,
penganiayaan itu memantik konflik massal. Konon, Roy Runtu melakukan
penganiayaan karena pengaruh minuman keras. Apa pun penyebab terjadinya
penganiayaan tersebut, tetap saja tidak mampu mendamaikan keadaan. Sebab,
pemuda-pemuda remaja masjid melakukan reaksi terhadap kasus yang menimpa Ridwan
Ramboni.
Itulah awal mula kejadian memilukan
yang memicu konflik berdarah di Poso tahun 1998. Isu-isu mengenai SARA kemudian
menghiasi konflik itu. Sehingga, sentimen agama tak terbendung lagi. Pada saat
itulah, panggung kekerasan tergelar. Darah tercecer. Poso mencekam.
Tragedi kemanusiaan di Poso jelas
merupakan potret nyata bahwa di satu sisi negeri ini masih “nyaman” dengan
situasi yang berujung pada pembunuhan. Kekerasan seolah menjadi jalan terakhir
yang harus ditempuh. Sedangkan di sisi lain, pemerintah gagal menjembatani
konflik berdarah tersebut. Sehingga, ke depannya, tragedi Poso masih berpotensi
meledak kembali. Entah dengan isu-isu apalagi.
Membaca konflik Poso jelas tidak hanya semata-mata
dari kacamata kesukuan. Artinya, kesukuan bukan masalah utama yang menjadi
sumber konflik. Meskipun kita tahu bahwa koflik Poso awalnya dilatarbelakangi
oleh masalah kesukuan dan kecemburuan sosial, akhirnya Kristen di Poso ingin
menegakkan satu aturan, yakni aturan Kristen, khususnya di daerah Tentena.
Tidak hanya itu, pihak Kristen juga ingin menjadikannya sebagai ibu kota dari
Kabupaten Pamona Raya yang murni mereka kelola.
Terlepas dari benar tidaknya pernyataan tersebut,
faktor politis memang harus dicurigai, karena Poso telah ditunggangi oleh
pihak-pihak yang berkepentingan (kaum pemodal). Banyak korporasi-korporasi
raksasa yang menjadikan konflik kekerasan di Poso sebagai keberkahan (blessing in disguise). Barangkali, itu
adalah proyek imperialisme terselubung. Sebagaimana dikatakan oleh Eggi
Sudjana, kita memang harus hati-hati dengan gaya baru imperialisme di mana kini
subjeknya tumpang tindih antara pelaku ekonomi swasta dan penguasa politik.
Dan, sepertinya itu terjadi di Ambon.
Barangkali, selama ini kita hanya melihat kekerasan
berdarah di Poso degan kacamata “kekerasan antar pemeluk agama”, tanpa melihat
adanya konflik-konflik struktural menyusul kehadiran korporasi-korporasi
raksasa. Karena itu, keinginan untuk membentuk sebuah kabupaten khusus bagi
orang Kristen juga berkait-berkelindan dengan keinginan para kapitalis domestik
dan global melalui korporasi-korporasi raksasa untuk menguasai kekayaan sumber
daya alam yang memang sangat melimpah di daerah itu.
Banyak pisau analisis yang digunakan untuk membedah
bagaimana memahami kejadian di Poso yang telah merenggut banyak korban, mulai
dari perspektif hubungan sosial antar-pemeluk agama hingga masalah korporasi
yang berperan di balik tragedi itu, sebagaimana dijelaskan tadi. Dari sekian
analisis terkait kekerasan di Poso, banyak yang sepakat bahwa negara telah
gagal dalam menciptakan ruang yang kondusif bagi masa depan Poso. Berkali-kali
jalur ditempuh oleh pemerintah, tapi Poso tetap bergejolak dan terus akan
bergejolak mungkin?
Dalam catatan lembaga Kontras, dalam konflik
kekerasan di Poso itu terdapat dua karakter yang berbeda. Pertama, konflik kekerasan yang terjadi secara terbuka. Pada masa
ini konflik dan kekerasan dilakukan secara masif, terorganisir dan menggunakan
identitas kelompok tertentu yang bisa dikenali oleh pihak lain. Kedua, kekerasan yang terjadi secara
tertutup. Pada masa ini, kekerasan dilakukan hanya melibatkan sejumlah kecil
orang, tidak tampak pergerakan massa secara masif. Sedangkan kesamaan dari
kedua konflik kekerasan itu ialah keterlibatan aparat keamanan, baik berupa
tindakan langsung (melalui individu atau unit atau kesatuan) maupun tindakan
tidak langsung, seperti pembiaran, pelepasan tersangka kekerasan.
Dengan demikian, dalam membaca kekerasan di Poso,
tidak adil jika kita hanya mengkritik warga sipil yang terlibat dalam konflik
itu dengan klaim bahwa mereka intoleran dan eksklusif-fanatik. Meskipun
kenyataannya demikian, kita juga harus membaca kembali komitmen yang diusung
pemerintah terkait dengan penanganan masalah Poso.
Pemerintah telah gagal karena berulang kali
peristiwa kekerasan terjadi di Poso. Bahkan, Human Right Watch, sebuah lembaga
pemantau hak asasi manusia, menilai terjadinya konflik berdarah di Poso
merupakan bentuk langsung kegagalan pemerintah pusat Indonesia selama empat
tahun. Dalam penelitian yang dipublikasikan di New York pada tanggal 4 Desember
2002 itu, sebagaimana dilansir Tempo, disebutkan bahwa lebih dari seribu orang
meninggal dan lebih dari 100.000 kehilangan tempat tinggal sejak konflik antara
umat Islam dan Kristen di Poso meletus pada Desember 1998.
Kegagalan pemerintah Indonesia di mata Human Right
Watch ialah membiarkan keamanan di kedua kubu tak terkendali. Sehingga,
tembakan dan serangan bom terus berlanjut begitu bebasnya. Selain itu,
pemerintah Indonesia dinilai gagal karena membiarkan para tersangka kerusuhan
bebas berkeliaran dan lolos dari jerat hukum.
Kini maka dari itu, pertanyaan yang layak kita ajukan
ialah, sampai kapan pemerintah akan menindak dengan tegas para pelaku pelanggar
HAM di Poso serta memberi keadilan bagi para korban dan keamanan sosial untuk
selanjutnya? Apakah hanya sekedar berlatarbelakang sosial-budaya bukan politik agama? Atau politik-politik lainnya? Apakah ini pembantaian terhadap satu agama saja? dan pertanyaan misterius lainnya. Tentunya kini menjadi tugas kita bersama untuk mencari tahu kebenaran di balik semua pertanyaan-pertanyaan itu.
“Memuliakan manusia, berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan
dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya.” – Gus Dur
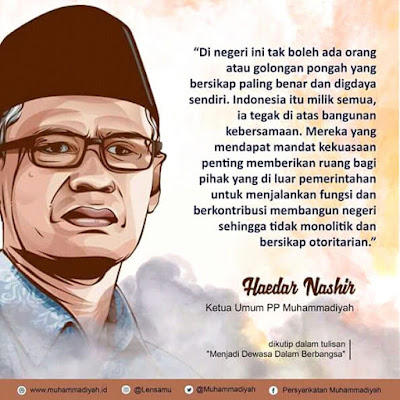


Komentar
Posting Komentar